Setiap setengah enam pagi, saya akan keluar rumah untuk menyapu jalan. Kejadian yang terjadi selalu sama. Seorang anak perempuan dengan jarak 1 rumah dari saya akan ikut menyapu juga. Lalu ada seorang ibu pulang dari pasar dengan motor vario. Tak lama kemudian, seorang ibu dengan jaket merah mengendarai sepeda menuju pasar. Ketika melewati saya, kedua ibu itu akan berkata, “Mbak…” dan saya menjawab, “Nggih…”. Selalu begitu.
Saya tidak tahu, kedua ibu itu di mana rumahnya, siapa namanya, dan kenapa memilih jalan ke pasar dengan melewati jalan depan rumah saya. Padahal masih ada jalan kampung yang lebih besar. Tapi, saya justru merasa dekat karena saling menyapa. Awalnya kami hanya tersenyum atau saling mengangguk ketika saya menghentikan menyapu dan membiarkan beliau lewat terlebih dahulu. Lama-lama, ibu itu mulai berani menyapa, walaupun memang hanya ‘mbak’ saja. Lucunya, kedua ibu itu tidak melakukan hal yang sama pada tetangga saya. Mungkin karena tetangga saya tetap saja menyapu dan tidak ambil pusing ketika kedua ibu itu lewat.
Kejadian serupa juga terjadi ketika saya memanaskan mesin motor saat berangkat agak pagi. Dua orang anak SD akan lewat sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Sapaannya lebih hangat, “Mbak, mau berangkat?”. Dan saya akan menjawab sambil tersenyum dengan hangat. Padahal mereka anak-anak kampung yang rumahnya agak jauh dari perumahan saya. Hanya kebetulan saja lewat karena SD mereka terletak di ujung rumah saya.
Tapi itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak orang yang lewat di depan atau di samping rumah. Sebagian besar akan tetap berlalu, walau mungkin mata sudah saling bertemu. Itu yang membuat miris. Saya tidak tinggal di perumahan elite, bahkan dekat dengan kampung yang masih terlihat sawahnya. Di alamat pun masih memakai embel-embel desa. Tapi budaya sapa rasanya mulai terkikis. Ada yang bilang, maklum ini perumahan para pekerja. Suami istri banyak yang berkarier, anak-anak sibuk sekolah, budaya pun mengikuti kota-kota metropolitan.
Padahal tidak juga. Saat saya di Depok dulu, setiap keluar kos, akan ada ibu-ibu asli Betawi yang bertanya, “Berangkat kuliah neng?” atau “Mau cari sarapan neng?”. Bahkan ketika saya akhirnya meninggalkan Depok, ibu itu berkata “Hati-hati ya neng. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya.” Itu cuma ibu tetangga kos saya yang asli Betawi. Suaranya saja cablak sekali. Malah yang sama-sama orang Jawa asli di samping kos saya, angkuhnya luar biasa.
Mengkhawatirkan juga. Jujur saja, mungkin saya tidak hafal nama pemilik rumah dalam radius beberapa puluh meter dari saya. Tapi kalau di desa, tetangga kampung yang jaraknya berkilo-kilo masih tahu siapa namanya dan bagaimana keluarganya. Rasanya memang menyedihkan. Tapi saya rasa ini bukan perkara desa atau kota. Ini perkara mau tidak kita membuka hati dan mata. Lalu membuka mulut untuk menyapa.
Terkadang tetangga samping rumah memang terasa lebih jauh dibanding tetangga jauh yang rela saling sapa. Mungkin itulah yang terbaik. Memanusiakan manusia dengan menyapa karena menganggap mereka benar-benar ada.
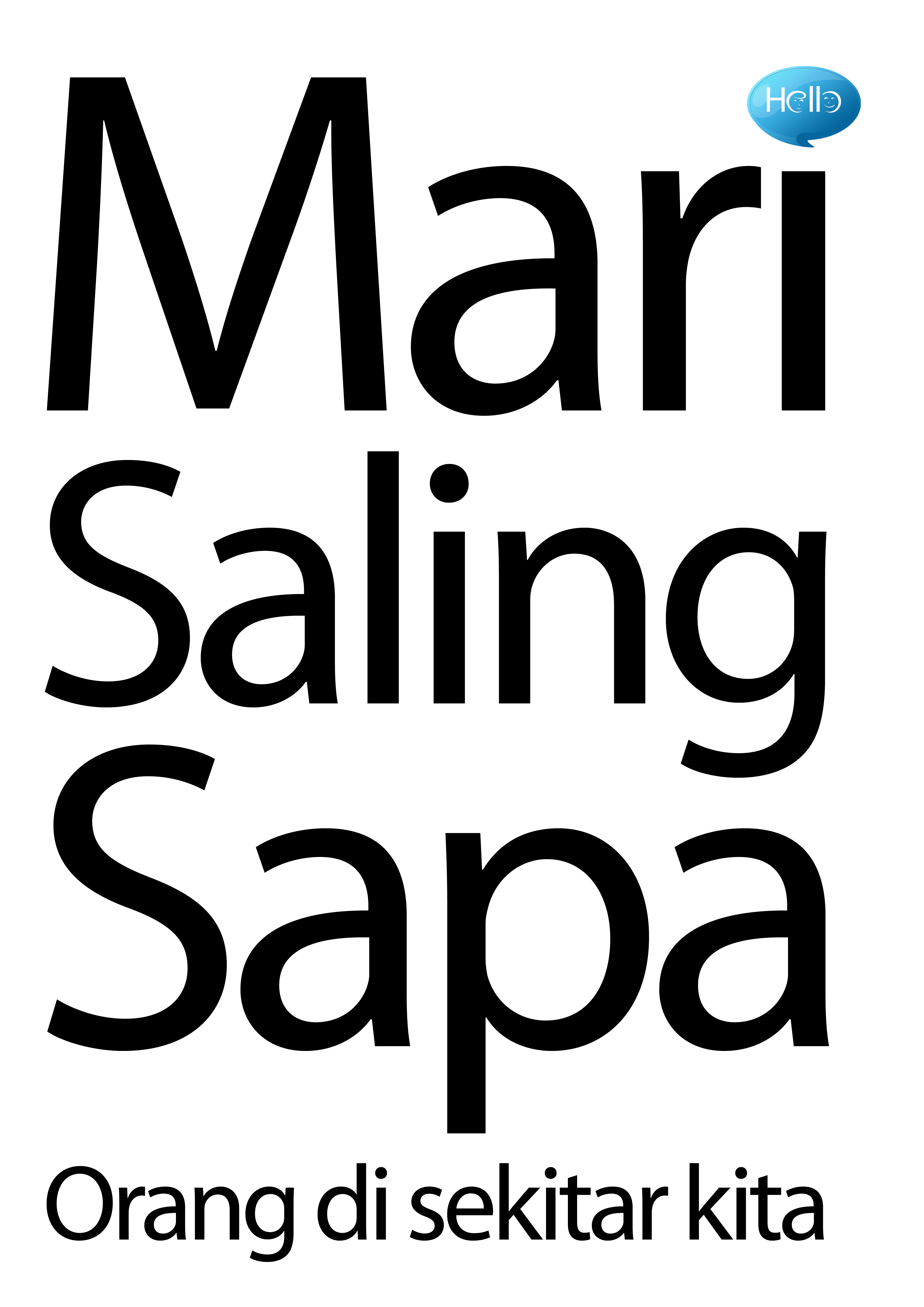



nice posting mbak..^^
ReplyDelete